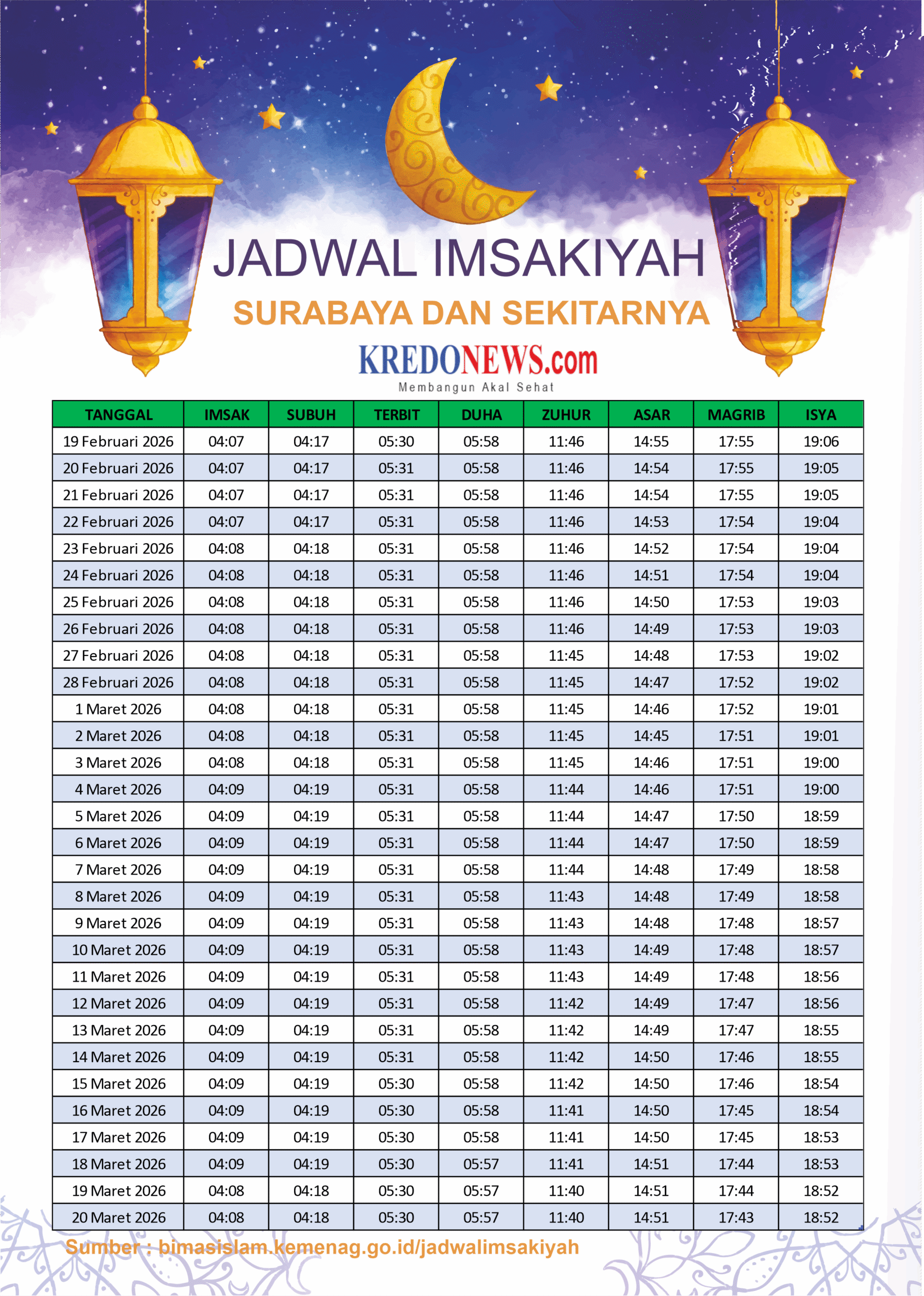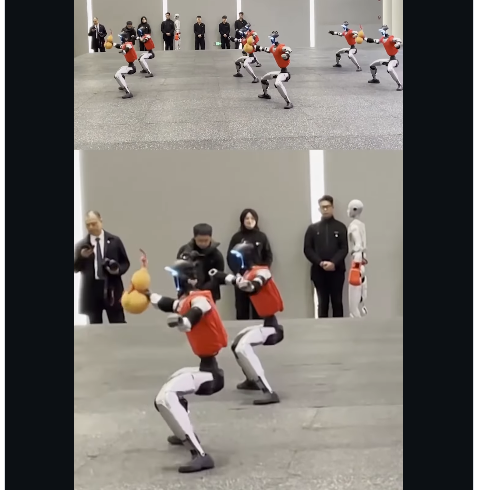Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan di bulan Oktober 2025
Terjemahan dari artikel asli: Turks in Gaza Will Mean Dead Americans
Oleh Michael Rubin*
Pada 11 September 2012, Duta Besar AS Chris Stevens berada di Konsulat AS di Benghazi, Libya. Ia bertemu Konsul Jenderal Turki Ali Sait Akın. Ternyata, itulah pertemuan terakhir sang duta besar dengan sang konsul.
Pertemuan itu sebetulnya peristiwa rutin. Tetapi ketika meninggalkan gedung sekitar pukul 20.30, Akin melewati sekelompok militan yang didukung oleh Turki berkumpul di konsulat tersebut. Akin melihat bahwa selain membawa senapan AK-47, orang-orang yang berkumpul itu membawa granat berpeluncur roket bahkan beberapa persenjataan yang lebih berat.
Akın tampaknya memilih untuk tidak memberi tahu Sean Patrick Smith, seorang staf Konsulat AS yang masih bersama Stevens dalam ruangannya.
Lebih dari satu jam kemudian, para militan yang berkumpul, menyerang Konsulat AS. Stevens termasuk salah satu korban yang tewas.
Belakangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mempromosikan Akin menjadi duta besar dan menempatkannya di Afghanistan. Di sana, ia bekerja untuk melibatkan, menormalisasi, dan memberdayakan Taliban.
Pada tahun 2012, banyak orang di Washington, D.C., terus saja mempercayai fiksi bahwa Erdoğan awalnya adalah seorang demokrat. Mereka yakin, Islamisme yang dihayati Erdoğan lebih merupakan peninggalan masa lalunya.
Daniel Fried, diplomat tertinggi Departemen Luar Negeri untuk Eropa bahkan menggambarkan Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin Erdoğan tak lebih dari versi Turki dari Partai Demokrat Kristen—yang religious. Jadi hanya skedar nama.
Sikap naif seperti itu kini seharusnya tidak boleh ada. Seiring dengan berhentinya konflik senjata di Gaza, ada pembicaraan tentang kontingen Amerika yang terdiri dari 200 orang di Israel untuk mendukung rekonstruksi Gaza.
Meski laporan awal menunjukkan bahwa pasukan Amerika tidak akan ditempatkan di Gaza, ada kemungkinan cukup besar kawasan itu bakal menjadi tempat transit mereka. Terutama mengingat Presiden Donald Trump ingin menjadikan Gaza sebagai basis warisannya, jika bukan pusat kampanyenya untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2026.
Pada saat yang sama, Trump tidak merahasiakan kekaguman dan persahabatannya dengan Erdoğan. Erdoğan, pada gilirannya, secara terbuka menginginkan Turki berperan di Gaza. Bukan sekedar karena kontrak konstruksinya menguntungkan, tetapi juga karena ia menganggap dirinya sebagai pelindung baru Hamas.
Erdoğan memang secara terbuka bersimpati kepada Hamas, tidak hanya terkait Israel, yang ia anggap sebagai negara teroris, tetapi juga terkait Otoritas Palestina.
Jika Trump memberi pijakan kepada Erdoğan di Gaza, makai ia akan menjadi jalur penyelamat Hamas dan kelompok ekstremis Islam lainnya. Jauh di luar pangkalan AS di Afghanistan, papan reklame Turki mempromosikan solidaritas Islamis alih-alih penjaga perdamaian NATO, rekonstruksi Afghanistan, atau demokrasi.
Di Libya, Turki terus mendukung faksi-faksi penganut Islam paling radikal yang berupaya mengalahkan kelompok-kelompok Libya yang lebih sekuler yang lebih memandang Mesir sebagai model.
Setiap rombongan Turki di Gaza bakal mempersenjatai Hamas atau penerus Islam radikalnya karena tiga alasan:
Pertama, memastikan Hamas tetap hidup dan untuk berjuang pada hari lain sekaligus mempertahankan posisinya yang terpenting sebagai warga Palestina yang mendekati masa transisi setelah Ketua Otorias Palestina berusia 89 tahun, Mahmoud Abbas, meninggal dunia.
Kedua, Gaza bakal digunakan sebagai pijakan melawan Israel. Dan ketiga, menjadikan Gaza sebagai alat untuk mengganggu Mesir dari timur maupun dari barat, tempat faksi-faksi Libya beroperasi.
Mempermalukan Amerika dengan membiarkan Hamas menculik atau membunuh personel Amerika akan menjadi bonus bagi Erdoğan, yang memandang Trump sebagai orang yang bisa dimanfaatkan, alih-alih sebagai teman yang harus dihormati.
Turki sudah siap menjalankan aksinya. Tiga belas tahun silam, negara itu mendorong terjadinya ekstremisme Islam, mendorong para pengemis untuk tahu cara menyerang sasaran sebelum menyerangnya kemudian mengabaikan para ekstremis yang membunuh seorang duta besar AS, maka apa yang mungkin mereka lakukan di Gaza bisa jadi lebih ekstrem lagi.
Jadi, hanya ada satu perbedaan antara Turki sekarang dan Turki pada tahun 2012. Yaitu bahwa kini Erdoğan sudah lebih bersedia mendukung terorisme sekaligus lebih yakin dengan kemampuannya untuk lolos dari hukuman.***
- Dr. Michael Rubin adalah senior fellow pada Lembaga kajian American Enterprise Institute. Ia memusatkan perhatian pada masalah Timur Tengah, khususnya Iran dan Turki. Ia pernah menjadi pejabat Pentagon dengan pengalaman luas di lapangan di Iran, Yaman dan Irak. Ia pernah pula terlibat dengan Taliban sebelum tragegi 11 September 2001. Selain sebagai penulis, dia juga mengajar pada Sekolah AL dan Marinis AS.