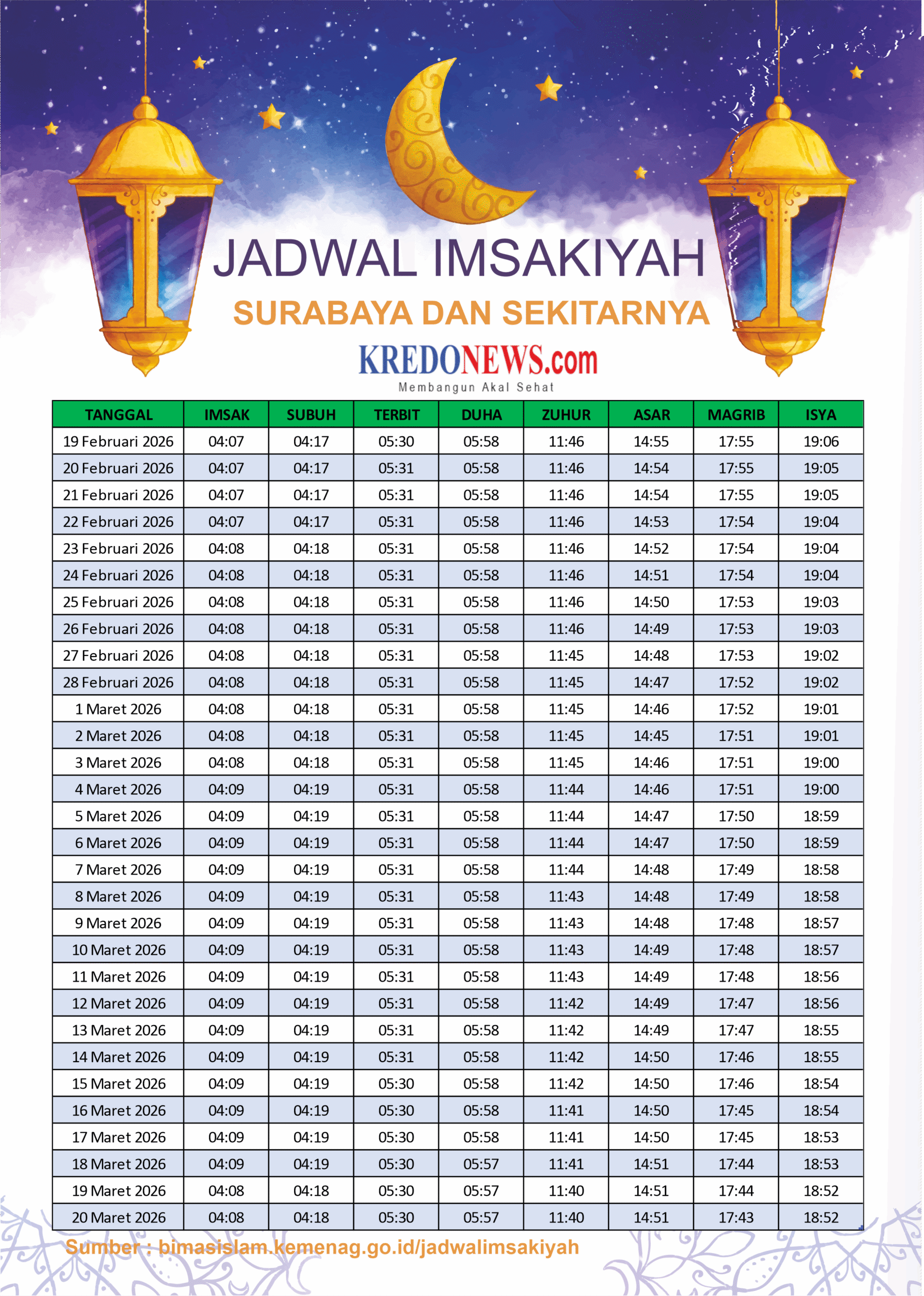Penulis: Saifudin | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWW.COM, SIDOARJO- Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, sejak Kamis sore, 2 Oktober 2025, mulai terdengar dentuman alat berat memecah kesunyian. Ini menandai babak baru dalam tragedi runtuhnya bangunan yang menewaskan santri.
Di balik suara mesin yang menggerus reruntuhan, tersimpan cerita perjuangan kemanusiaan yang menggetarkan hati.
Sebelum “sang raksasa besi” dikerahkan, tim SAR gabungan terlebih dahulu melalui proses mengharukan: tiga kali asesmen menyeluruh dalam kurun 10 jam, berjuang di atas tumpukan beton yang memilukan.
“Kami tidak akan berhenti sampai yakin tidak ada lagi nyawa yang tersisa,” ujar Kepala Subdirektorat RPDO Basarnas, Emi Freezer, dengan suara berat. Pukul 23.00 Rabu malam, 02.00 dini hari, dan 07.00 pagi—tim menyisir puing menggunakan detektor kehidupan dan anjing pelacak. Hasilnya? Nihil. Setiap kali alat berbunyi sunyi, seolah harapan ikut terkubur.
“Keputusan menggunakan alat berat adalah yang terberat. Ini bukan sekadar operasi, tapi melepas keinginan terakhir kami untuk menemukan korban selamat,” tambah Freezer, matanya berkaca-kaca mengingat detik-detik terakhir asesmen.
300 Kantong Jenazah
Di balik prosedur standar, terdapat persiapan yang menyayat hati. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memimpin penyiapan kekuatan luar biasa: 219 petugas terlatih, 300 kantong jenazah, 30 ambulans, dan 5 crane raksasa—semua siaga di lokasi seperti pasukan menghadapi perang.
“Setiap kantong jenazah yang kami bawa adalah doa agar korban bisa pulang dengan layak. Setiap crane adalah janji kami untuk mengakhiri penderitaan keluarga yang menunggu,” ujar Suharyanto.
Ia menjelaskan proses evakuasi akan berjalan bertahap dan penuh kehati-hatian: “Setiap lapisan puing diangkat crane, tim akan turun tangan kembali memastikan tak ada tanda kehidupan. Ini ritual kehormatan bagi mereka yang telah pergi.”
Dilema
Di antara suara mesin dan debu beton, terlihat sosok-sosok petugas yang terpaksa mengubur harapan. Seorang anggota tim SAR terlihat memeluk erat sesama rekan setelah asesmen ketiga—isyarat bahwa perjuangan mencari keajaiban harus berakhir.
“Kami tahu keluarga masih berdoa di pengungsian. Tapi tugas kami kini berubah: memastikan korban ditemukan dengan martabat,” tutur seorang relawan yang enggan disebut namanya.
Sore itu, saat crane pertama mengangkat balok betulang, seorang ibu tertunduk di pengungsian. Ia tak menangis—hanya menggenggam foto anaknya yang masih berseragam putih ponpes. Di kejauhan, terdengar adzan maghrib berkumandang, seolah menyapa ruh-ruh yang tengah dicari.
Tragedi Al Khoziny meninggalkan pelajaran: di tengah reruntuhan fisik, ada kekuatan manusia yang tak runtuh—ketulusan menolong, keberanian menghadapi kenyataan, dan keikhlasan melepas. Tim SAR bukan sekadar “petugas evakuasi”. Mereka adalah pahlawan yang memastikan cinta lebih kuat dari beton.
“Kami pulangkan mereka bukan sebagai korban, tapi sebagai insan yang dihormati. Itu janji kami.”
—Tim SAR Gabungan, di atas puing-puing Ponpes Al Khoziny. **