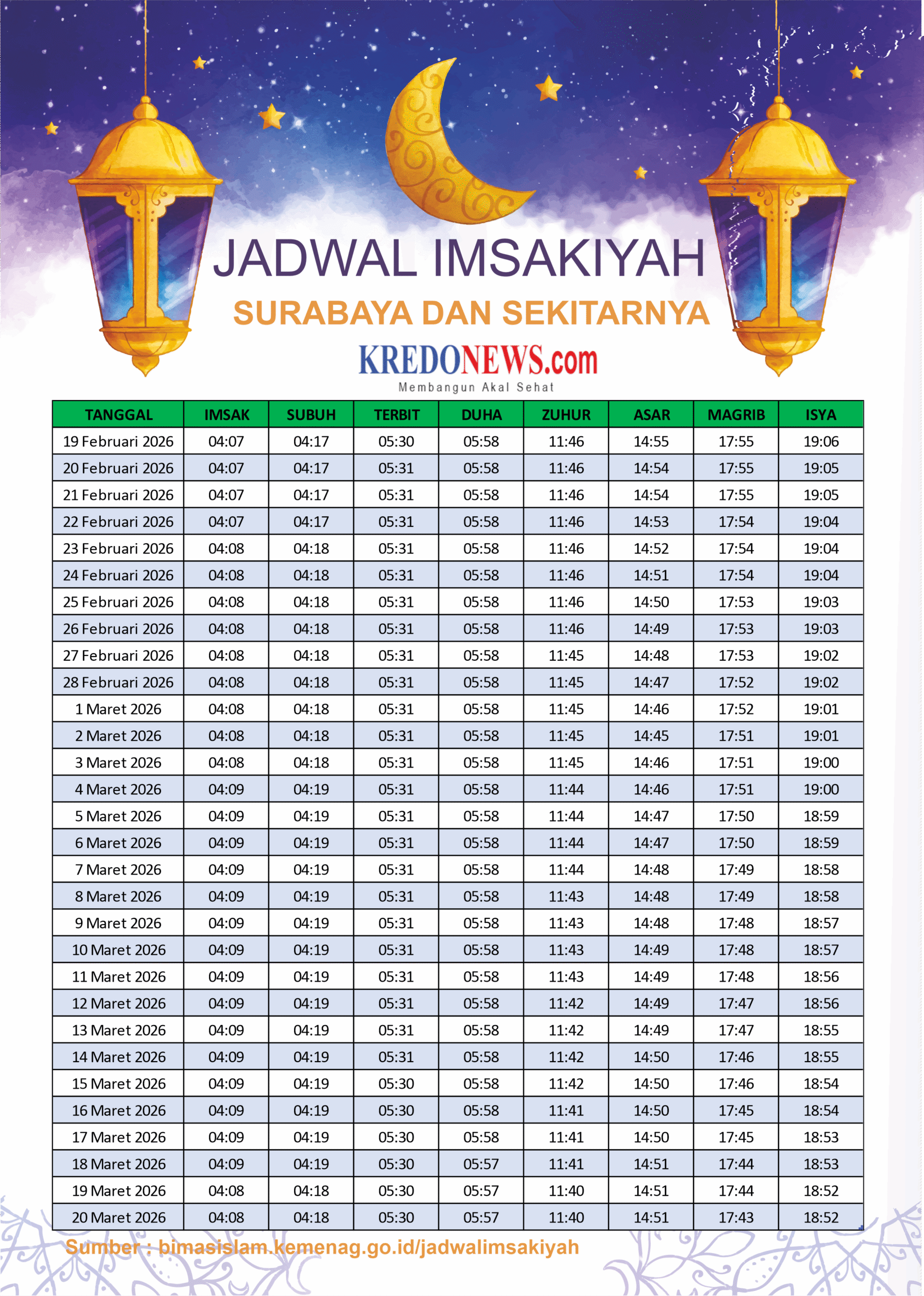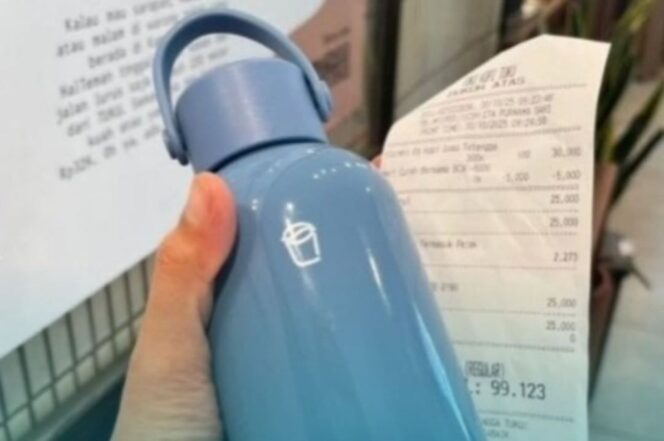Penulis: Jacobus E Lato | Editor: Yobie Hadiwijaya
KREDONEWS.COM, JAKARTA-Di era ketika gaya hidup hijau jadi tren, kepedulian terhadap bumi sering kali dikaitkan dengan belanja. Tumbler warna pastel, tote bag dengan slogan ramah lingkungan, hingga sedotan stainless yang dibungkus cantik—semuanya seolah menjadi tiket masuk ke komunitas “eco-friendly”.
Genta, seorang pemerhati isu keberlanjutan, melihat fenomena ini dengan kritis. “Mereka membuat kita merasa bahwa cara menunjukkan kepedulian adalah melalui pembelian. Pesannya sederhana, kalau kamu peduli lingkungan, belilah ini,” ujarnya. Kata-kata Genta menohok: kepedulian yang seharusnya lahir dari kesadaran, kini dikemas jadi komoditas.
Kelas menengah, dengan ritme hidup serba cepat, cenderung mencari solusi praktis. Membeli produk hijau terasa lebih mudah dibanding mengubah gaya hidup atau mendorong aksi kolektif. Akibatnya, keberlanjutan sering direduksi menjadi sekadar pilihan konsumsi.
Wika, salah satu konsumen, merasakan dilema ini secara langsung. Ia pernah punya enam tumbler, semua dibeli karena takut ketinggalan tren. “Aku jadi mikir, sebenarnya kalau terus-terusan FOMO ikuti tren, itu enggak bakal ada habisnya,” katanya. Kesadaran itu membuatnya berhenti menambah koleksi. “Sekarang aku nanemin, apa yang sudah punya ya itu dulu. Kalau sudah rusak baru beli lagi.”
Cerita Wika adalah cermin banyak orang: niat baik yang berubah jadi pola konsumsi baru. Padahal, esensi keberlanjutan bukan soal berapa banyak barang hijau yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mengubah cara hidup.
Genta menutup refleksinya dengan tegas. “Sejatinya, menyelamatkan lingkungan bukan persoalan membeli produk apa, tetapi mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi secara menyeluruh.”
Pesan itu sederhana tapi kuat. Bumi tidak butuh kita belanja lebih banyak, bumi butuh kita berpikir ulang: apakah benar kepedulian bisa dibeli, atau justru harus diwujudkan lewat perubahan nyata dalam keseharian.***